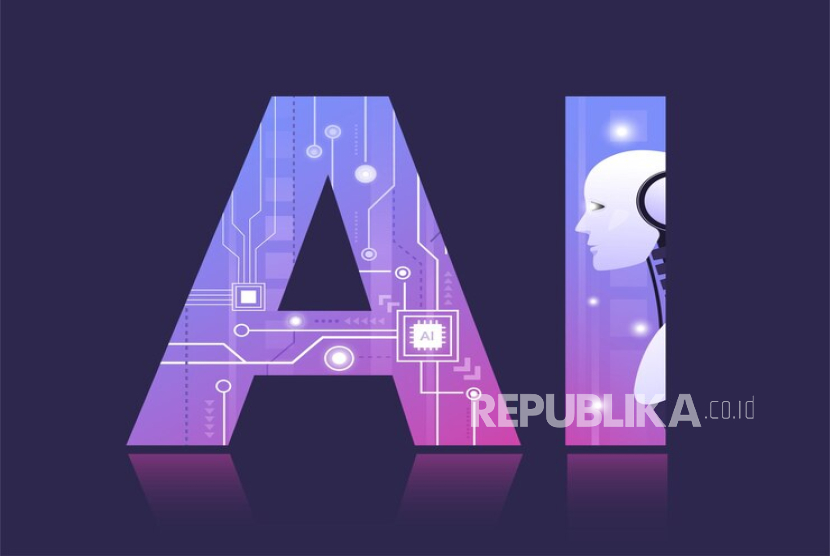Oleh : Budi Purwanto, Dosen dan Kepala Kantor Manajemen Risiko IPB University
REPUBLIKA.CO.ID, Mengapa risiko tetap terjadi meski organisasi sudah memiliki standar operasional prosedur, matriks risiko, dan tim pengendali? Jawabannya seringkali tidak terletak pada sistemnya, melainkan pada cara kita berpikir.
Manajemen risiko (MR) selama ini cenderung dipahami sebagai urusan dokumen, checklist, atau pelaporan. Padahal, banyak kegagalan besar justru berasal dari bias pikiran, asumsi keliru, dan ketidakmampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman.
Contohnya sederhana: seorang pimpinan yang terlalu percaya diri bisa menyepelekan risiko yang nyata. Sebaliknya, tim yang terlalu takut gagal justru bisa melewatkan peluang penting. Keduanya sama-sama terjebak pada cara berpikir yang tidak disadari, atau dalam istilah ilmu perilaku disebut bias kognitif.
Herbert Simon, peraih Nobel, menyebutnya bounded rationality: manusia membuat keputusan bukan secara rasional penuh, tapi dengan “akal praktis” yang dibatasi oleh informasi, waktu, dan kapasitas berpikir. Kita tidak selalu tahu bahwa kita tidak tahu. Dan itulah akar dari banyak risiko yang tidak pernah terdeteksi.
Itulah sebabnya, manajemen risiko hari ini perlu bertransformasi menjadi manajemen kognitif: sebuah pendekatan yang menempatkan pikiran manusia sebagai pusat dari pengambilan keputusan dan pengendalian risiko.
Alih-alih hanya mengisi matriks risiko, organisasi perlu:
- Membiasakan tim melakukan pre-mortem: membayangkan skenario kegagalan di awal proses agar bisa dicegah.
- Mengkaji bias umum dalam pengambilan keputusan: seperti overconfidence atau groupthink.
- Melatih kesadaran risiko secara reflektif dan berbasis pembelajaran, bukan hanya kepatuhan formal.
Pendekatan ini disebut oleh para ahli sebagai Cognitive Risk Management: mengelola risiko dengan memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan belajar dalam menghadapi ketidakpastian.
Paradigma ini juga menekankan pentingnya budaya belajar dan berbagi pengetahuan. Organisasi yang belajar dari kesalahan secara terbuka akan lebih cepat beradaptasi dibanding organisasi yang hanya fokus menutupi kelemahan.
Penerapan teknologi seperti AI dan big data memang penting, tapi tidak boleh menghapus peran akal sehat dan pemahaman manusiawi. Dalam banyak kasus, krisis terjadi bukan karena kurangnya data, tetapi karena kurangnya kebijaksanaan menafsirkan data itu sendiri.
Karena itu, manajemen risiko harus lebih dari sekadar instrumen teknis. Ia adalah bagian dari pembentukan budaya organisasi yang sehat secara berpikir dan berakhlak. Risiko bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dengan memahami cara pikir kita sendiri—dan membuka ruang untuk saling mengingatkan dan belajar—organisasi akan lebih tangguh, adaptif, dan bermartabat.
Sebagai bangsa, kita mengenal ungkapan musibah datang karena kelalaian atau kesombongan. Dalam bahasa manajemen, musibah sering berakar dari pikiran yang tertutup, asumsi yang tak diuji, dan ego yang tak dibendung.
Sudah saatnya kita kembali ke akar: menjadikan akal sehat dan hikmah sebagai pondasi pengambilan keputusan, baik dalam bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan. Dan manajemen risiko—yang selama ini hanya menjadi lampiran—seharusnya menjadi pusat dialog strategis: bagaimana kita berpikir, belajar, dan membuat keputusan yang benar sebelum risiko menjadi kenyataan.