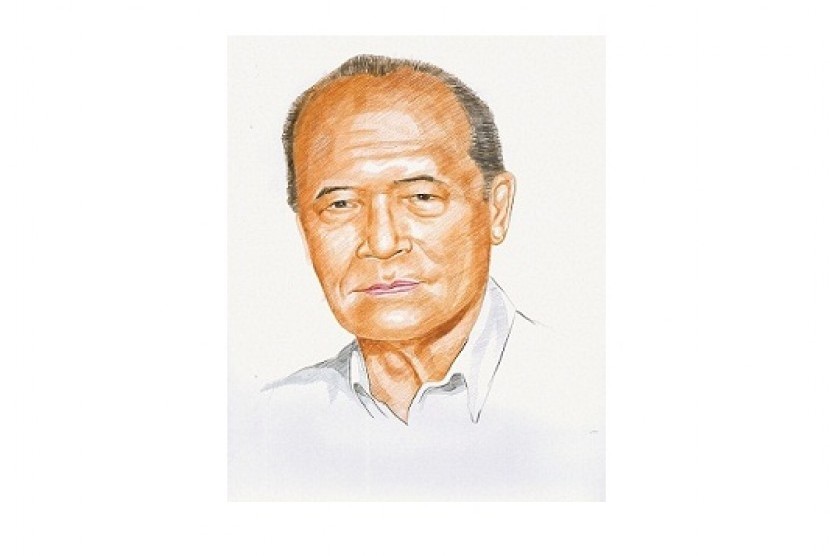REPUBLIKA.CO.ID, Jika ditinjau dari sisi ajaran Alquran tentang merebaknya konflik politik dan sektarianisme berkepanjangan di dunia Muslim dalam skala kecil atau skala besar, kita akan gagal menemukan satu ayat pun dalam Kitab Suci ini yang dapat digunakan sebagai alasan pembenaran. Tetapi mengapa umat Muslim hampir sepanjang sejarah tidak pernah bosan bertikai dan bahkan berperang antara satu sama lain? Akarnya bisa dicari tidak lama pasca wafatnya nabi Muhammad SAW saat kader-kader inti beliau terlibat dalam konflik itu, sebagaimana yang akan dibicarakan nanti. Telah muncul semacam Arabisme salah jalan (misguided Arabism) di masa awal itu yang ironisnya berlangsung sampai hari ini.
Artikel penulis Turki kontemporer Mustafa Akyol dalam The New York Times¸ 3 Feb. 2016, menguatkan pernyataan di atas: “Agama sesungguhnya bukanlah menjadi pokok utama dari konflik-konflik ini—selalu saja, politik yang mesti disalahkan. Tetapi penyalahgunaan Islam dan sejarahnya menyebabkan konflik politik ini menjadi semakin buruk, saat partai-partai, pemerintah, dan milisia mengklaim bahwa mereka berperang bukan untuk kekuasaan atau wilayah tetapi atas nama Tuhan. Dan ketika musuh dikatakan sebagai kelompok yang menyimpang (heretics) bukan hanya sebagai lawan, maka perdamaian menjadi sukar untuk dicapai.” Sebagian besar bangsa Arab sekarang sedang berada dalam iklim yang serba rentan ini. Konflik politik dan sektarianisme menjadi pemicu utamanya. Perasaan kita pastilah sangat prihatin dengan fenomena ini. Jika demikian, di mana Alquran?
Akibat penempatan lawan bukan sekadar musuh, tetapi sebagai orang yang telah keluar dari rel agama berdasarkan doktrin fanatisme subjektif satu pihak, maka radius permusuhan sesama Muslim tidak diragukan lagi akan sulit dibendung dan dikendalikan. Orang tega saja “menyeret” Tuhan ke pihaknya dengan cara nista dan tidak bertanggung jawab. Inilah doktrin faksi khawarij yang mencuat ke permukaan sejarah sejak 657 masehi sebagai salah satu akibat Perang Shiffin yang melibatkan elite Arab Muslim masa awal dengan aktor utamanya ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, keduanya dari suku Quraisy.
Ajaibnya, doktrin destruktif ini dibiarkan bertahan selama ratusan tahun sampai detik ini. Mengapa? Analisis di bawah akan mencoba menjelaskannya, sekalipun mungkin baru pada tingkat hipotesis. Terus terang saja, menghadapi masalah rumit ini, kadang-kadang saya merasa berada di jalan buntu, tidak tahu lagi bagaimana mengurainya bila ditempatkan dalam parameter ajaran.
Jika dalam Perang Onta pada 656 masehi, sekalipun telah terlibat di dalamnya kader-kader inti nabi, tragedi ini belum melahirkan sekte-sekte keagamaan yang berhimpit dengan politik kekuasaan. Perang Shiffin adalah drama awal yang tragis yang memicu polarisasi komunitas Muslim dalam bentuk: sunni, syi’ah, dan khawarij. Di ruang ini, saya telah menulis tentang masalah ini lebih dari sekali.
Sebagai produk sejarah konflik politik elite Arab Muslim, maka sunnisme, syi’isme, dan kharijisme telah merasuk jauh ke ranah teologi, fikih, dan teori politik dengan pendukungnya masing-masing. Arabisme salah jalan itulah yang diekspor ke seluruh jagat raya selama berabad-abad, tidak saja oleh Muslim Arab, tetapi Muslim non-Arab juga turut serta dalam gelombang penyebaran faham pemicu perpecahan ini. Seakan-akan yang serba Arab itu pastilah benar, karena Alquran sebagai al-furqân (pembeda antara yang benar dan yang salah) tidak pernah diajak berunding dalam merumuskan peta persoalan.
Sampai hari ini, Muslim non-Arab ternyata tidak punya tapisan yang ketat untuk menilai Arabisme dalam kategori ini berdasarkan kriteria Alquran yang difahami secara benar dan kontekstual. Situasi menjadi semakin runyam, karena Muslim yang non-Arab itu pada umumnya tidak mampu mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya dalam bahasa Arab. Maka ketergantungan rumusan Islam dalam bungkus Arabisme itu tidak dapat dielakkan lagi. Bagi saya, meneruskan cara beragama semacam ini sama saja dengan melanggengkan malapetaka dan penderitaan bagi umat ini.
Untuk masa depan, di saat peradaban Arab Muslim sedang berada pada titik nadir akibat perang saudara yang teramat parah di kawasan itu, apakah belum waktunya untuk menampilkan sebuah corak Islam yang bebas dari racun Arabisme yang salah jalan itu? Kerja besar dan menantang ini sungguh memerlukan kecerdasan dan keberanian luar biasa dari pemikir Muslim non-Arab dengan syarat penguasaan sumber-sumber Islam dalam bahasa aslinya benar-benar dipersiapkan oleh berbagai perguruan tinggi Muslim di berbagai belahan dunia ini. Melalui upaya ini, siapa tahu, umat pada saatnya akan menemukan kembali jati-dirinya yang sejati dengan pimpinan Alquran untuk selanjutnya mampu keluar dari kotak Arabisme dan sektarianisme yang destruktif itu.