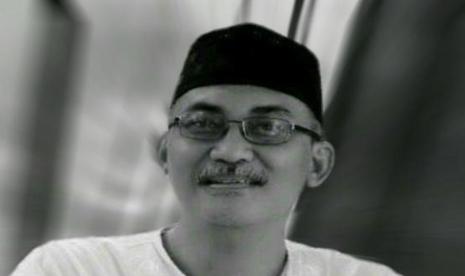
Oleh : Heka Hertanto, Praktisi CSR Artha Graha Peduli
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- History repeats by itself. Kalimat itu identik dengan isu dan perkembangan yang selalu terulang dengan aktor yang berbeda, namun substansi tetap sama. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan linearitas periode per 100 tahun secara spesifik, namun berbagai kejadian global tetap terus berulang dalam kisaran kurang dari atau lebih dari 100 tahun.
Dunia, mencatat, bencana alam besar bisa berulang lagi pada masa siklus 100 tahun. Siklus krisis 100 tahun adalah konsep yang menggambarkan peristiwa besar seperti pandemi, perang, dan krisis ekonomi cenderung terjadi setiap sekitar 100 tahun. Beberapa teori, seperti teori generasi Strauss-Howe, membahas siklus panjang 80-100 tahun ini, sementara ahli lain menyoroti krisis yang lebih sering terjadi seperti krisis 10 tahunan.
Sementara Teori Siklus yaitu konsep ini sering didasarkan pada teori siklus sejarah atau ekonomi yang melihat pola berulang dalam masyarakat dan perekonomian. Kini Indonesia menghadapi "krisis ekonomi sunyi" yang ditandai dengan pelemahan daya beli, anjloknya penjualan retail, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meskipun secara makroekonomi tidak terjadi krisis finansial besar seperti tahun 1998 akibat langsung dari Krisis Moneter Asia, yang menyebabkan PHK massal di berbagai sektor, termasuk konstruksi dan perbankan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga, ketidakpastian ekonomi global, dan kebijakan defisit APBN yang berimbas pada penurunan belanja pemerintah ke daerah, sehingga menyebabkan kenaikan pajak daerah.
Kembali pada Teori Siklus 100 tahun seperti meledaknya wabah korela pada tahun 1820, lalu pada tahun 1920 ada Flu Spanyol yang menewaskan lebih dari 50 juta warga di seluruh dunia. Selanjutnya bergeliat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan virus corona yang mempengaruhi seluruh dunia dan mengakibatkan jutaan warga dunia merenggut nyawa. Secara sains, penyebab mencuatnya pandemi ini berbeda, namun dunia mengalami pandemi besar dalam siklus waktu yang relatif konsisten di dunia medis.
Sejalan dengan wabah, hal serupa juga terjadi pada paku bumi yakni Bencana vulkanik besar yakni erupsi Gunung Tambora di Sumbawa NTB pada tahun 1815 yang menyebabkan “Tahun Tanpa Musim Panas” pada 1816 akibat debu vulkanik yang menyelimuti atmosfer. Selanjutnya disusul erupsi Gunung Krakatau di Pulau Rakata Selat Sunda pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami besar dan mengubah iklim global, dan menewaskan lebih dari 36.0000 orang. Erupsi Gunung Pinatubo di Pulau Luzon Philipina pada tahun 1991. Erupsi besar dari gunung api menyebabkan pendinginan global karena sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Siklus letusan gunung berapi besar terjadi dalam rentang sekitar 100 tahun atau lebih. Memang tidak tepat terjadi setiap 100 tahun sekali.
Masalah besar lain di dunia ini yakni perang antara negara. Misalnya Perang Napoleon pada tahun 1815 yang menyebabkan kekalahan Napoleon Bonaparte dalam Pertempuran Waterloo dan ini mengakhiri dominasinya di Eropa. Selanjutnya ada Perang Dunia I pada tahun 1914-1918 sebagai konflik global pertama yang melibatkan banyak negara dan mengubah tatanan politik dunia. Seratus tahun kemudian, meletus Perang modern dan ketegangan global yakni Perang Dingin dan ketegangan geopolitik pada abad ke-21 menunjukkan pola serupa dengan perang besar sebelumnya.
Patut dicatat, setiap 100 tahun, dunia mengalami konflik besar yang mengubah peta politik global. Sering kali perang terjadi karena masalah perut, memperebutkan sumber ekonomi. Krisis ekonomi besar cenderung terjadi dalam pola yang mirip setiap 100 tahun. Krisis Keuangan pada tahun 1825 adalah krisis besar pertama di dunia modern karena spekulasi keuangan yang berlebihan. Lalu meluncur depresi besar pada tahun 1929-1939 yang menyebabkan kehancuran finansial di berbagai negara. Sekitar 100 tahun kemudian, terjadi lagi krisis keuangan pada tahun 2008 yang berdampak global yang mirip dalam mengguncang sistem ekonomi dunia. Fluktuasi ekonomi besar ini menunjukkan bahwa ada pola krisis besar yang terjadi dalam siklus panjang.
Meskipun bencana alam atau malapetaka krisis ekonomi global tidak selalu berulang secara persis dalam siklus 100 tahun, peristiwa besar seperti pandemi, letusan gunung berapi, perang, dan krisis ekonomi memiliki pola waktu serupa. Ini menunjukkan bahwa sejarah seringkali memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana dunia menghadapi tantangan yang terus berulang dari masa ke masa.
Bagaimana dengan kesiagaan Ibu Pertiwi memitigasi berbagai bencana alam hingga krisis ekonomi? Pernyataan Indonesia "diambang krisis" merujuk pada kekhawatiran yang timbul dari beberapa tantangan ekonomi dan sosial yang saling terkait, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian politik. Kondisi ini diperburuk oleh dampak global yang belum terselesaikan dan isu domestik. Meskipun bukan krisis moneter besar seperti 1998, beberapa pakar melihat adanya tanda-tanda krisis yang berpotensi terjadi di masa depan.
Potensi krisis yang diidentifikasi yakni Krisis ekonomi meliputi perlambatan ekonomi nasional akibat pelemahan ekspor, penurunan permintaan domestik, dan masalah ketenagakerjaan seperti PHK. Selanjutnya krisis sosial seperti ketimpangan sosial yang melebar antara si kaya dan si miskin. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan layak, terutama di daerah terpencil. Ketidakpuasan akibat pembangunan yang dianggap tidak merata.
Masalah selanjutnya, krisis politik yaitu munculnya berbagai masalah yang berkaitan dengan penurunan nilai-nilai demokrasi. Peningkatan konflik antara publik dan pejabat negara yang didorong oleh ketidakadilan sosial ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterlambatan dalam program keberlanjutan yang dapat mengancam posisi global Indonesia. Krisis lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan.
Tidak dapat dibantah lagi, kekhawatiran krisis di Indonesia merupakan cerminan dari akumulasi berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
Di Indonesia, tanda-tanda krisis ekonomi seperti pelemahan daya beli terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tercermin dari rendahnya jumlah pemudik saat Lebaran dan tren masyarakat yang lebih berhemat. Seiring dengan melemahnya daya beli Masyarakat yaitu anjloknya penjualan retail: Penjualan retail dan sektor usaha kecil mengalami penurunan, di mana masyarakat mengurangi pengeluaran untuk hal-hal non-esensial seperti pergi ke kafe atau berbelanja online. Serta tsunami PHK: Puluhan ribu pekerja di sektor manufaktur dan sektor lainnya kehilangan pekerjaan akibat efisiensi perusahaan yang merugi dan tidak mampu menjual hasil produksi.
Masih berkaitan dengan tanda-tanda krisis di RI yakni Pemerintah mencatat defisit APBN pada awal tahun 2025, yang berdampak pada pemangkasan biaya transfer ke daerah. Pajak daerah naik: Defisit ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pungutan pajak, yang menjadi salah satu pemicu aksi protes masyarakat.
Melemahnya kepercayaan konsumen: Indikator kepercayaan konsumen menurun di awal tahun 2025, karena masyarakat merasa khawatir kehilangan pekerjaan dan khawatir terhadap kenaikan harga. Penyebab utama krisis yakni kebijakan efisiensi pemerintah untuk memangkas biaya transfer ke daerah, yang kemudian memicu kenaikan pajak daerah yang tinggi. Ketidakpastian ekonomi global: Kondisi ekonomi global yang tidak pasti, termasuk kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara maju, memengaruhi nilai tukar rupiah dan investasi.
Dampak krisis ekonomi di RI adalah meningkatnya risiko kesehatan masyarakat: Pendapatan berkurang membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan, serta stres karena tekanan ekonomi yang memengaruhi kesehatan mental. Melemahnya dunia usaha: Banyak UMKM yang menjadi korban utama, sementara perusahaan besar juga mengalami penurunan margin keuntungan, memaksa mereka untuk menunda ekspansi dan membuka cabang.
Solusi
Kita harus memutus mata rantai tidak terjadinya krisis ekonomi Nusantara dengan pemberian stimulus ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah lesunya konsumsi masyarakat. Stimulus untuk memacu pertumbuhan: Perlu stimulus untuk memacu pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama memanfaatkan efek musiman di momen-momen seperti awal tahun.
Kedua, peningkatan daya beli melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Peningkatan partisipasi masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan berdialog lebih sering dengan masyarakat.
Pada hakikatnya bencana alam, bencana ekonomi bahkan bencana kegaduhan politik dan lain-lain tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang tidak disadari oleh para intelektual atau pengambil kebijakan. Memang manusia tidak bisa mencegah terjadi bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung, gelombang tsunami, dan sebagainya namun manusia bisa mengurangi dampak bencana tersebut melalui mitigasi untuk mengurangi manusia menjadi korban atau harta benda. Edukasi kepada warga untuk peduli pada lingkungan sehingga sudah ada antisipasi evakuasi kala bencana menyapa warga. Bencana alam bisa terjadi setiap tahun tanpa harus menunggu siklus 100 tahun.
Memang, secara ilmiah masih menjadi perdebatan. Gagasan siklus 100 tahun sering kali muncul dari kebetulan historis, seperti rentetan pandemi besar (wabah pes pada 1720-an, kolera pada 1820-an, Flu Spanyol pada 1920-an, dan COVID-19 pada 2020-an), namun para ilmuwan tidak menemukan mekanisme global tunggal yang mengatur semua jenis bencana alam dalam siklus 100 tahun yang rapi.
Namun, meskipun tidak ada siklus yang menetapkan per 100 tahun secara detail, tetap saja fenomena, terutama krisis ekonomi harus dapat diantisipasi mengingat potensi krisis tetap ada, terlebih lagi saat ini kita berada pada berbagai persoalan ekonomi yang memperburuk pola hidup dan meningkatkan permasalahan sosial.
Isu konflik Laut Tiongkok Selatan, memanasnya isu Indo-Pasifik, PDB Indonesia yang tidak meningkat secara signifikan, jumlah pengangguran yang terus meningkat, trend penggunaan senjata biologis untuk kepentingan militer, dan persoalan-persoalan lainnya dapat menjadi pemicu trend siklus per 100 tahun terjadi mengingat setiap pihak tentu berupaya mencapai kepentingan dengan atau tanpa mengorbankan pihak lain.
Terlebih lagi apa yang baru saja terjadi di Aceh. Perubahan iklim dan banjir besar di wilayah tersebut juga merupakan dampak dari kerusakan alam yang terus berulang akibat dari perilaku manusia yang cenderung eksploitatif terhadap alam, yang berdampak pada 3.057 jiwa dari 2.070 kepala keluarga. Hal itu menjelaskan dampak bencana alam yang terjadi akibat perilaku yang terus berulang sehingga memicu bencana alam. Hal ini menjelaskan bahwa proses terjadinya bencana alam menjadi kejadian alam yang terus berulang.
Bencana alam dan perilaku manusia saling berhubungan, di mana perilaku manusia dapat memperburuk dan memicu bencana alam, seperti banjir akibat membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan liar. Faktor pelaku (manusia) tidak berubah, sementara alam terus menjadi objek eksploitasi. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa manusia selalu hadir dengan sikap egoisme sementara alam terus tumbuh, hancur, dan kemudian tumbuh lagi untuk siap dihancurkan kembali.
Seperti yang disampaikan penyair Romawi Plautus pada abad ke-2 SM bahwa Homo Homini Lupus yang berarti "manusia adalah serigala bagi sesamanya", yang menggambarkan pandangan suram tentang sifat manusia yang dapat menjadi predator dan menyakiti satu sama lain. Ungkapan ini merujuk pada potensi kekejaman, egoisme, dan agresi manusia, di mana individu bertindak seperti serigala yang memangsa sesamanya untuk keuntungan atau kelangsungan hidup.
Ungkapan ini pula yang menggambarkan bahwa dunia selalu berputar di poros persoalan yang sama, yaitu kekejaman, keegoisan dan manusia pula sebagai pelaku dari setiap kerusakan di muka bumi ini, baik dari periode dahulu, sekarang, dan akan datang, dengan pelaku, isu, dan dampak kerusakan yang berbeda pula namun dengan persoalan yang selalu sama, yaitu ekonomi, sosial, pandemik, perang dan persoalan-persoalan yang menyangkut hidup umat manusia.


