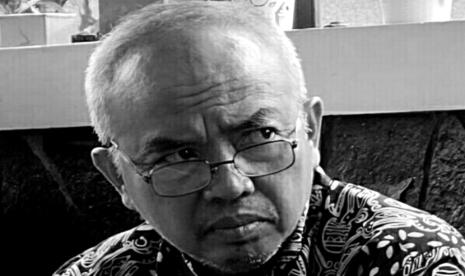
Oleh : Achmad Tshofawie; Kordinator Ecofitrah, Keluarga ICMI dan FKPPI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frasa “natural resources” pertama kali dipopulerkan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, dalam konteks ekonomi politik klasik, terutama oleh pemikir seperti Adam Smith, Thomas Malthus, dan David Ricardo.
Namun, pencetus sistematis pertama yang memakai dan menormalisasi istilah itu secara luas adalah George Perkins Marsh (1801–1882),seorang diplomat, ekolog awal, dan penulis buku "Man and Nature" (1864).
Frasa “natural resources” (sumber daya alam) adalah kata yang kehilangan jiwa. Begitu kita menyebut sungai sebagai ‘sumber daya’, kita sedang menyiapkannya untuk dieksploitasi.
Bahasa menentukan moralitas.Jika sungai adalah “resource”, maka manusia adalah “user”. Tapi jika sungai adalah “being” (makhluk hidup), maka manusia adalah “neighbor” atau “guardian”.
Jika kita kesulitan membayangkan sungai sebagai “hidup”, maka lihatlah apa yang terjadi saat sungai “mati” (ikan terapung, aliran kering, ekosistem runtuh).
Dengan menganggap sungai sebagai “yang hidup”, maka relasi manusia-alam bergeser: dari penguasa/pengguna menjadi peserta, mitra, bahkan bagian dari aliran.
Dalam Alquran; bumi, air, dan gunung tidak pernah disebut “resources”, melainkan ayat -- tanda-tanda Allah (QS Fussilat:10, QS Al-Mu’minun:18–19).
Jadi, dalam pandangan Qurani, istilah “natural resources” justru merupakan penyimpangan semantik dari konsep amanah dan ayat-kauniyah.
Jika kita menolak istilah “natural resources” karena mereduksi alam menjadi stok material, maka secara epistemologis dan etis, istilah “human resources” (SDM) juga layak dikoreksi, bahkan dalam pandangan Qurani bisa dikategorikan sebagai penghinaan halus terhadap martabat insan.
Asal-usul Istilah “Human Resources”
Istilah ini lahir pada awal abad ke-20, dalam konteks Taylorisme dan manajemen industri. Pertama kali dipopulerkan oleh John R Commons dalam karya “The Distribution of Wealth” (1893),lalu semakin mapan lewat E Weight Bakke (1940-an) dan Peter Drucker (1950-an).
Tujuannya: menata manusia di pabrik dan perusahaan sebagai komponen produktif setara mesin, modal, dan bahan baku. Maka lahirlah frasa yang hingga kini kita dengar setiap hari:“Mengelola sumber daya manusia.” (Seolah manusia adalah bahan bakar pabrik ekonomi.)
Mengapa Istilah Ini Bermasalah?
Secara bahasa dan filsafat, “resources” berarti sesuatu yang dapat dipakai, habis, dan diganti. Maka, human resources secara implisit menempatkan manusia dalam posisi:
instrumen ekonomi, bukan tujuan;
komponen sistem, bukan subjek moral.
Konsekuensinya serius. Nilai manusia diukur dari produktivitas, bukan pengabdian atau niat. Martabat manusia direduksi menjadi kapital kerja. Lahir budaya korporat yang efisien tapi kehilangan ruh, karena manusia hanya dianggap “tenaga”, bukan “amanah”.
Perspektif Qurani dan Fitrah
Dalam Alquran, tidak pernah manusia disebut resource. Sebaliknya, Allah menegaskan, “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam…” (QS Al-Isra’: 70)
Manusia bukan resource, tapi makhluk yang dimuliakan dan diamanahi,bukan untuk “digunakan”, tapi untuk “menjadi”. Manusia adalah ‘abdullah (hamba Allah) dan khalifah fil ardh (pemakmur bumi), bukan unit produksi.
Jadi kalau natural resources menurunkan nilai bumi,maka human resources menurunkan nilai manusia.
Wallahu’alam


