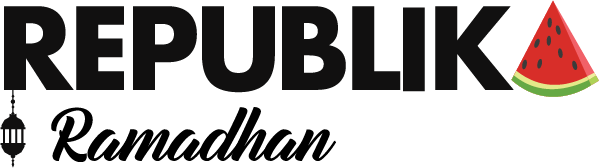Oleh : Ilham Tirta, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 43,3 persen masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap data Covid-19. Hasil survei terbaru Charta Politika (Kamis, 12/8) itu begitu mencengangkan di tengah maraknya aturan pembatasan jarak sosial yang dilakukan pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat seakan tidak terpengaruh oleh daya rusak varian Delta yang digembar-gemborkan pemerintah, tepat ketika responden menjawab pertanyaan surveyor pada 12-20 Juli 2021.
Data itu muncul setelah lebih dari satu tahun Indonesia menyatakan perang terhadap Covid-19. Sudah begitu banyak energi yang terbuang, baik ekonomi maupun kesehatan, dalam melawan penularan bala penyakit dari Kota Wuhan, Cina tersebut. Lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat telah gugur. Resesi ekonomi pun tak terbantahkan. Namun, semua itu tidak akan berarti ketika patisipasi masyarakat menunjukan angka minim.
Penulis sengaja memberi garis besar tulisan ini dengan 'Titik Nol Covid-19'. Bukan ingin mengembalikan kita kepada diskusi panjang terkait salah dan tidaknya penanganan pandemi. Penulis ingin sedikit mengulas akar pesoalan dari titik terbawah pranata sosial kita, yaitu desa. Bukankah Charta Politika juga menarik responden dari 120 desa dalam mengabil kesimpulan di atas?!
Penulis meyakini ada sejumlah alasan kenapa masyarakat banyak menolak mempercayai data pemerintah. Bukan saja data, kalau mereka ditanyakan lebih ke dasar, maka mereka tidak akan ragu menyatakan 'Tidak percaya adanya Covid-19'.
#Kepanikan melahirkan persepsi yang salah
Pada April-Mei 2020, masyarakat Indonesia, dari kota hingga pedesaan jauh, tersihir oleh Covid-19. Kekhawatiran akan tularan virus mematikan diikuti oleh memberlakuan pembatasan sosial masyarakat oleh pemerintah pusat hingga daerah. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker adalah keharusan. Masyarakat pun patuh!
Kepatuhan yang mahal setelah mereka menyaksikan berbagai video dan informasi di media sosial yang menampilkan keganasan virus corona. Salah satunya, orang-orang yang tetiba kejang, lalu jatuh, dan tewas di tempat. Begitu sadis dan mengerikan. Meski video itu telah dinyatakan hoaks atau kabar bias, namun kepercayaan itu sudah melekat: bahwa corona yang disebut pemerintah itu bukan sembarang penyakit.
"Lihat saja di sini, orang hidup normal, tidak ada yang pakai masker, tapi tidak ada orang yang meninggal secara sadis seperti itu. Itu menandakan corona itu hanya ada di media (pernyataan pemerintah)," kata salah seorang yang diajak penulis diskusi terkait Covid-19 di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Juni 2021.
Perlu diketahui, penilaian warga yang sebut saja namanya Dwi (33 tahun), sarjana jurusan matematika, ini mungkin mewakili sebagian besar masyarakat di desanya, bahkan desa-desa tetangganya. Lebih luas lagi kecamatan dan masyarakat Bima dan Kota Bima pada umumnya. Pada Juni itu, sesaat sebelum Delta mengamuk di Jawa dan Bali, jarang sekali ada orang yang memakai masker, apalagi menjalankan prokol kesehatan lainnya. Toko dan pusat perbelajaan beroperasi dengan normal. Pemerintah daerah dan jajaran aparat seperti polisi dan TNI juga jarang terlihat seperti di kota-kota besar.
Kebanyakan masyarakat seperti Dwi menanggalkan kepatuhannya karena merasa ada yang janggal dengan virus mematikan itu. Di awal pandemi, bukan saja masyarakat yang panik, namun juga para nakes di Rumah Sakit. RS awalnya memakai standar umum, yaitu masyarakat yang memiliki gejala corona akan langsung diisolasi. Akibatnya, banyak orang yang hanya karena panas atau sekadar batuk biasa harus diisolasi. Mereka kemudian dinyatakan negatif Covid-19 hanya beberapa hari setelanya.
"Orang jatuh dari motor disebut corona, orang hamil disebut corona. Puluhan orang diisolasi, tapi langsung negatif lagi dalam waktu sehari. Katanya penyakit berbahaya, sampai orang-orang tidak bisa bekerja, shalat saja diatur," kata warga Bima lainnya.
Akumulasi dari kekecewaan itu membuat masyarakat memilah informasi yang mereka konsumsi. Kebanyakan menolak membaca, menonton, dan berbicara soal Covid-19. Kalaupun sakit, mereka menolak dirujuk ke RS, kecuali yang sudah sekarat. Berapa pun banyaknya korban Covid yang dirilis pemerintah hari ini, mereka benar-benar tidak peduli.
Menurut penulis, apa yang terjadi di daerah itu adalah masalah serius yang harus ditangani. Ada kesalahan masyarakat dalam memahami apa itu Covid-19. Sementara, pemerintah daerah dan aparatnya tampak apatis. Penulis menduga, pemda, khususnya pemerintah Kota dan Kabupaten Bima hanya menunggu data korban Covid dari rumah sakit. Tidak tampak adanya tindak lanjut dari data orang yang terpapar tersebut, seperti tracing (pelacakan) dan testing (tes) kontak erat pasien yang seharusnya dilakukan.
Pada Juli hingga Agustus ini, Kota Bima dan sebagian kecamatan di Kabupaten Bima ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Setiap hari ada warga yang meninggal karena Covid-19, kebanyakan karena ketiadaan oksigen. Namun, masyarakatnya tetap acuh.
Menurut seorang petugas di RSUD Sondosia, Kecamatan Bolo, Bima, saat-saat ini, banyak yang sakit tetapi tidak dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di rumahnya masing-masing. Semua gejalanya hampir sama, yaitu corona. Saat tulisan ini dimuat, kematian Covid di RS tersebut sudah mencapai angka puluhan. RSUD Sondosia sedang bersiap dikhususkan untuk pasien Covid-19.
#Merembet ke vaksinasi
Ketidak pedulian terhadap Covid-19 merembet pada tingkat kepercayaan terhadap vaksin. Jika saja dosis vaksin sudah tersedia melimpah, maka akan ketahuan berapa presentasi masyarakat yang enggan divaksin. Bukan saja isu halal dan tidaknya vaksin, namun mereka telah percaya vaksin adalah produk asing untuk melemahkan rakyat Indonesia. Mereka melihat Indonesia, bukan dunia!
Penulis melihat langsung bagaimana program vaksinasi Pemkab Bima di setiap desa pada akhir Juli lalu. Saat jadwal penyuntikan, banyak masyarakat yang memilih pergi ke ladang, kebun, dan gunung. Bukan untuk bekerja, melainkan......