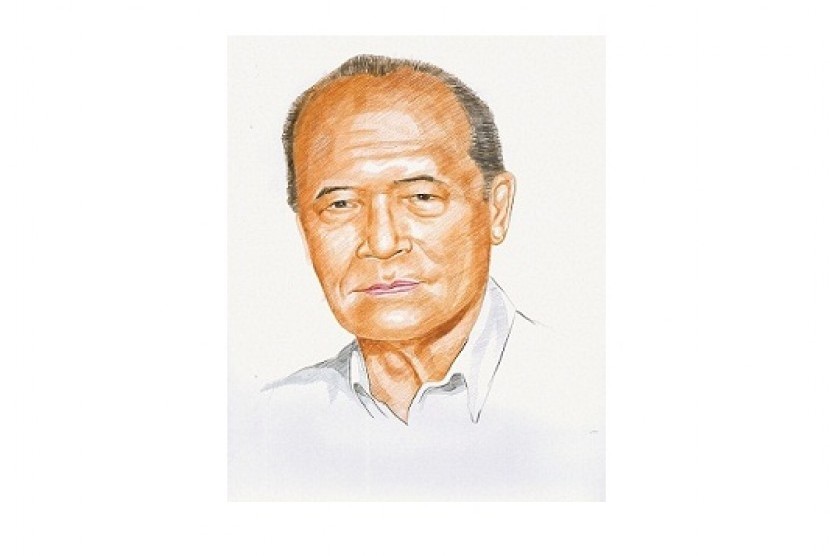REPUBLIKA.CO.ID, Jauh sebelum Indonesia merdeka hampir 72 tahun yang lalu, para pendiri bangsa sudah berbicara tentang dua kekuatan nasional kembar yang tidak bisa dipisahkan: nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi. Nasionalisme politik bertujuan untuk mengubah status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, dan cita-cita mulia itu telah tercapai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tonggak 17 Agustus adalah deklarasi lahirnya sebuah negara baru di gugusan kepulauan Nusantara: negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh.
Sekalipun harus bertempur selama empat tahun antara 1945-1949 dalam kancah revolusi nasional, karena penjajah Belanda masih tidak mau hengkang dari negeri ini, akhirnya dengan korban yang tidak sedikit, kita menang. Belanda baru pada Desember 1949 bersedia mengakui negara baru ini, karena memang tidak punya pilihan lain lagi. Konstelasi politik global telah berubah secara drastis, sistem penjajahan harus diakhiri. Atau dalam ungkapan Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Dengan kemerdekaan bangsa ini, nasionalisme politik tidak berarti telah rampung dengan tugasnya. Sama sekali belum, karena untuk mengisi kemerdekaan bangsa nasionalisme politik harus bergandengan tangan dengan saudara kembarnya berupa nasionalisme ekonomi. Fasal 33 UUD 1945 (sebelum amendemen) dengan tepat memberi dasar konstitusional untuk nasionalisme ekonomi ini. Di bawah Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 itu memerintahkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ironisnya, sila kelima Pancasila berupa: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang antara lain dijabarkan dengan rinci dalam Pasal 33 itu tidak berjalan mulus setelah batang usia republik ini hampir mendekati 72 tahun. Ini sebuah kelalaian konstitusional yang harus dikoreksi secara berani dan tegas, jika kita memang ingin melihat bangsa ini benar-benar merdeka 100%, sebuah ungkapan yang selalu diteriakkan Tan Malaka di masa revolusi kemerdekaan. Nasionalisme ekonomi telah lama dibungkam oleh perusahaan-perusahaan asing dengan modal hampir tanpa batas atas penguasaan mereka di ranah perbankan, pertambangan, telekomunikasi, perkebunan, dan jangan lupa di industri asuransi jiwa terutama.
Kita tengok selintas perusahaan asuransi. Tulisan Wan Ulfa Nur Zuhra dalam medsos di bawah judul “Asing Mencengkram Industri Asuransi Jiwa” (26 Juli 2016) membeberkan betapa dahsyatnya gurita asuransi asing itu menguasai industri perasuransian Indonesia. Dikatakan bahwa dari total aset asuransi jiwa senilai Rp. 368,5 triliun, sebesar 74,37% adalah milik asing, seperti P.T. Prudential Life Assurance (barasal dari Inggris), P.T. AIA Financial (Hong Kong), P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Kanada), P.T. Asuransi Allianz Life Indonesia (Jerman), dan berapa lagi milik bangsa-bangsa Timur Jauh lainnya seperti P.T. Great Eastern Life Indonesia, P.T. Hanhwa Life Insurance Indonesia, dan P.T. Tokio Marine Life Insurance.
Di sisi lain, ada dua perusahaan asuransi milik orang Indonesia: P.T. Asuransi Jiwa Bumiasih dan P.T. Asuransi Jiwa Nusantara telah dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permintaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akibatnya, yang menjadi korban adalah para pemegang polis yang telah membayarkan premi sebelumnya menjadi hangus begitu saja. Kasus ini telah semakin memperburuk citra perusahaan asuransi lokal, padahal asuransi milik nasional itu masih ada yang bagus, seperti P.T. Asuransi Wahana Tata dengan 70 kantor dan 1.200 karyawannya di seluruh Indonesia. Kemudian P.T. Asuransi Bumi Putera 1912, industri asuransi tertua di Indonesia, nafasnya sedang Senen-Kamis. Semoga pembenaan total yang sedang berjalan sekarang terhadap asuransi ini akan bisa menyelamatkan perusahaan ini yang dulu adalah ikon di dunia asuransi nasional.
Tidak berbeda dengan nasib asuransi nasional, dunia perbankan, perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, dan lain-lain juga telah “tergadai” kepada pihak asing. Data dalam medsos dari tulisan Suardi dengan judul “Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing” (15 Feb. 2016) memberikan angka-angka di bawah ini sebagai bukti telanjang betapa imperialisme ekonomi itu telah mencekik leher bangsa ini. Penguasaan asing atas industri perbankan sudah berada pada angka 70%, pertambangan 85%, otomotif 99%, perkebunan 60%, telekomunikasi 70%, jasa 70%, tanah 93% (konglomerat Indonesia plus asing), minyak dan gas 88%.
Angka penguasaan tanah 93% itu adalah sebuah lampu merah tanda bahaya serius, dibagi antara konglomerat Indonesia dan asing berbanding menjadi 80%:13%. Lalu yang tersisa untuk rakyat Indonesia lain yang jumlahnya lebih dari 250 juta hanya tinggal 7%. Saya tidak tahu persis apakah angka-angka ini cukup valid, tetapi andaikan berbeda, selisihnya tidak akan terlalu banyak.
Jika demikian realitas getirnya yang diawali sejak Orde Baru (1966-1998) dan berlanjut sampai sekarang, maka pertanyaan panasnya adalah: di mana Pancasila, di mana Fasal 33 UUD? Pertanyaan ini harus dijawab segera oleh pemerintah JKW-JK dan elite Indonesia secara keseluruhan. Atau kita harus siap-siap untuk menjadi bangsa kuli yang hina-dina di muka bumi, tetapi sering dihibur dengan demo itu?