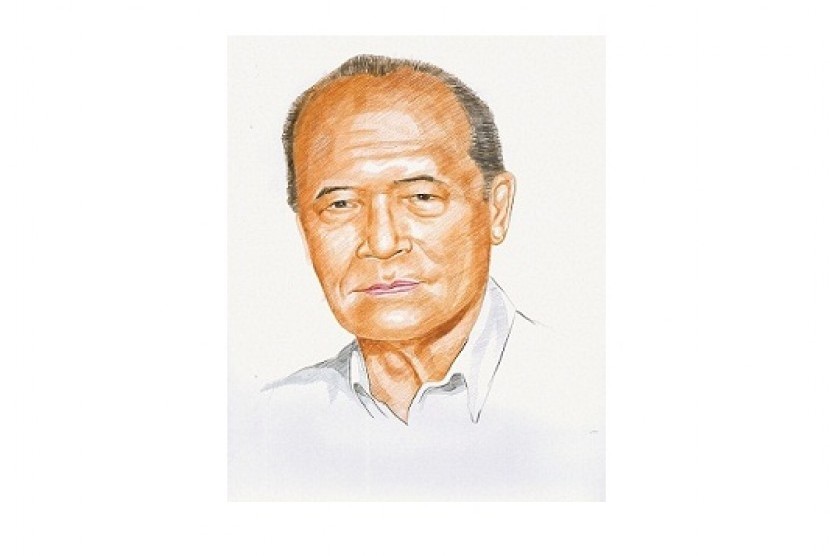REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Kepekaan berasal dari perkataan peka yang berarti mudah merasa karena perasaan yang halus. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1994), salah satu makna perkataan peka adalah mudah sekali merasa. The Oxford Dictionary of Current English (1992) yang dieditori RE Allen, kata sifat sensitif (peka) a.l. berarti acutely affected by external stimuli or mental impressions, having sensibility to (sangat terpengaruh oleh rangsangan luar atau impresi mental, punya keterharuan atau kepekaan terhadap).
Lawannya adalah tumpul (dull) atau majal atau mati rasa, tidak peka. Contoh dalam kalimat ini: “Nuraninya sudah lama tumpul terhadap kritik masyarakat.” Contoh lain, misalnya, “Karena terlalu lama bergelimang dalam dosa dan dusta, kepekaan jiwanya sudah lumpuh.”
Mengapa seseorang kehilangan kepekaan dan nuraninya menjadi majal terhadap kebenaran, kejujuran, kehalusan, tanggung jawab, dan rasa keadilan? Tentunya ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, kemiskinan yang parah dapat membawa orang pada keputusasaan, hilangnya perasaan malu, dan timbulnya mata gelap, sekalipun banyak juga orang miskin yang berhati lembut dan santun.
Kedua, karena kerakusan terhadap benda dan kekuasaan. Ini jelas jauh lebih berbahaya dan lebih akut dari yang pertama. Kerakusan dalam masyarakat kita sekarang, menurut seorang pengamat, telah sampai menyundul langit, telah menghancurkan batas dan pematang.
Ketiga, karena sistem birokrasi dan sistem hukum kita yang memberi peluang dan merangsang orang untuk kehilangan kepekaan nurani. Budaya mumpung (mumpungisme) yang sudah agak lama bersama kita semakin memperburuk situasi. Gerakan Reformasi tahun 1998 punya semboyan anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tetapi karena kepekaan semakin menghilang, maka tiga penyakit sosial tidak lagi bisa dibendung. Akibatnya, demokrasi yang dicita-citakan agar menjadi sehat dan kuat malah menjadi tawanan KKN itu.
Mumpungisme secara sosiologis bergandeng erat dengan nepotisme dengan berbagai wajah: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nepotisme memperkuat akar mumpungisme dan membunuh potensi kreativitas manusia yang tidak kebagian. Akibatnya, sinisme dalam masyarakat terhadap tatanan yang ada semakin merajalela.
Mereka yang tidak kuat iman boleh jadi akan melakukan apa saja untuk menyalurkan rasa dongkolnya terhadap realitas ketidakadilan dan kerakusan yang semakin transparan dalam masyarakat kita. Adapun mereka yang bisa menahan diri umumnya menjadi pasrah terhadap keadaan dan berharap siapa tahu suatu hari akan ada juga perubahan.
Bila harapan itu tidak juga kunjung menjadi kenyataan, mereka hanya berucap, ”Ini memang sudah nasib, mau diapakan lagi.” Inilah di antara bentuk skeptisisme sebagai akibat dari ketidakberdayaan.
Mumpungisme sebagai simbol dari kerakusan manusia yang selalu mencari celah untuk berbuat yang busuk dan onar, bisa juga mengundang munculnya radikalisme di kalangan masyarakat yang merasa tertindas oleh perilaku anomali ini. Kaum radikal ini tidak jarang menggunakan simbol-simbol agama sambil berteriak keras untuk melawan perilaku menyimpang itu, tetapi cara-cara yang mereka gunakan tidak kurang ganasnya, seperti tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat luas.
Dengan jargon memberantas kemungkaran, mereka pun sering memakai cara-cara yang mungkar yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan pertimbangan akal sehat. Semua fenomena hitam ini adalah pertanda bahwa fabrik sosial kita sedang terancam oleh kelakuan sebagian penduduknya yang tunamoral dan tunaakal sehat.
Mengenai orang yang rakus, baik terhadap benda maupun kekuasaan, Alquran dalam surah al-Takatsur ayat 1-2 menggambarkan: “Berlebih-lebihan (dalam harta, kesenangan, dan kekuasaan) telah melalaikan kamu. Hingga kamu masuk kubur. Jangan begitu, toh nantinya kamu akan tahu (akibat buruknya).”
Nurani yang sudah kehilangan kepekaan dan mati rasa sulit sekali untuk dapat membayangkan akibat buruk ini, sekalipun semuanya pasti berlaku. Inilah manusia dan inilah dunia! Harta dan kekuasaan itu ibarat orang minum air laut, semakin direguk semakin dahaga, sampai sebuah batas yang tidak dapat diterjang lagi: maut.
Indonesia benar-benar mendambakan munculnya pemimpin yang peka terhadap jeritan penderitaan rakyat. Semoga hasil Pilpres 9 Juli 2014 ini akan memenuhi harapan yang sudah lama dinantikan itu.