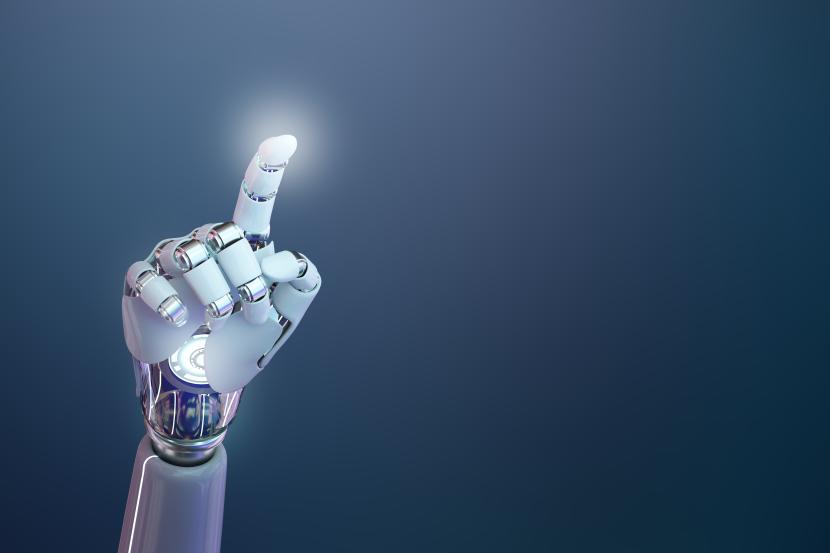Oleh : Muhammad Muchlas Rowi*
REPUBLIKA.CO.ID, LAS VEGAS -- TIDAK ada yang abadi, apa pun di dunia terus berubah [fluks universal]. Perumpamaannya seperti yang dikatakan Heraclitus, “one cannot step in to the same river twice.” Dari dulu hingga sekarang, tidak ada yang permanen.
Bedanya, perubahan sekarang terjadi lebih cepat gegara didorong disrupsi ganda akibat revolusi industri dan pandemi. Sehingga dunia begitu cepat berubah, arus uang dan barang juga berubah. Perusahaan bisnis makin mengadopsi teknologi digital, efisiensi dan inovasi makin dapat ditingkatkan.
Perubahan super cepat ini bisa kita lihat berdasarkan data Startup Ranking, perusahaan statistik asal Peru, yang melihat peningkatan luar biasa dalam jumlah perusahaan rintisan [startup] di dunia dalam satu dekade terakhir. Jumlahnya, kata mereka, ada sebanyak 148.549.
Negeri Mr. Trump menempati posisi puncak dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 78.073 startup. Kemudian, ada India yang menempati urutan kedua, dengan jumlah 16.302 startup. Lalu, Inggris di posisi ketiga dengan total 7.079 startup.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak di dunia, catatan mereka per 11 januari 2024 terdapat 2.562 startup di Indonesia. Jumlahnya paling banyak se-Asia Tenggara, peringkat ke-2 di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global.
Di Balik Kemajuan
Salah satu faktor yang membuat penambahan startup begitu cepat adalah keberadaan artificial inteligence atau AI. Karena disinyalir dapat menyederhanakan proses, mendapatkan wawasan berharga dari data, dan mengembangkan solusi inovatif yang memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.
Ketika pasar AI terus berkembang, startup yang secara efektif mengintegrasikan AI ke dalam strategi mereka. Peluang pun jadi lebih luas, tak cuma meningkatkan pertumbuhan namun juga berkontribusi pada transformasi industri dan lanskap bisnis secara keseluruhan.
Hanya saja, ini bukan berarti bebas risiko. Semua mata harus dibuka lebar-lebar, karena tidak ada kemajuan yang tanpa risiko. Dan dalam lingkungan dimana perubahan terjadi begitu cepat, risiko juga lahir secara berlipat ganda dan bisnis bermetamorfosis menjadi lebih kompleks. ‘There is no progress without risk.’
Ini terlihat dari Survei Artificial Intelligence Index Report 2024 oleh Stanford University, yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia termasuk yang paling optimis di dunia terhadap teknologi AI.
Tingkat optimisme masyarakat Indonesia terhadap teknologi Ai mencapai angka 78%. Disusul Thailand dan Meksiko di posisi dua dan tiga dengan tingkat optimisme sebesar 74% dan 73%.
Anehnya, tingkat optimisme masyarkat Indonesia, Thailand dan Meksiko ini berbanding terbalik dengan masyarakat Amerika Serikat, yang notabene merupakan pusat pengembangan Ai itu sendiri.
Mereka bisa dikatakan lebih khawatir dan pesimistis dengan meningkatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan bisnis. Hampir semua orang dewasa As [45%] mengatakan mereka sama-sama khawatir.
Alasan mereka rata-rata adalah soal potensi kehilangan pekerjaan, pertimbangan privasi dan prospek bahwa perkembangan AI akan melampaui keterampilan manusia. menyebabkan hilangnya hubungan antarmanusia, disalahgunakan atau terlalu diandalkan.
Fakta aneh lain, tingginya optimisme terhadap penggunaan Ai masyarakat Indonesia ternyata tak sejalan dengan index kesiapan pemerintah yang masih berada di peringkat 42. Bahkan jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia. Amerika meski masyarakatnya tak terlalu optimis, namun menjadi negara paling siap dalam hal penggunaan Ai [87,32]. [Government Ai Readiness Index, 2023].
Tsunami kebangkrutan
Kekhawatiran masyarakat Amerika atau negara-negara maju lainnya sebetulnya punya alasan kuat. Terutama jika melihat tingkat insolvensi antarnegara yang selain diakibatkan oleh kondisi ekonomi, kelembagaan, juga oleh tingkat kemampuan dalam memanfaatkan penggunaan Ai.
Pada tahun 2023, statista.com menyebut Prancis menjadi negara dengan tingkat kebangkrutan bisnis terbanyak di dunia, dengan hampir 60.000 kebangkrutan pada tahun tersebut. Semenatra di Tiongkok, meski menjadi negara yang cukup massif mengembangkan Ai, namun kebangkrutan bisnis meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hampir empat kali lipat sejak tahun 2015, mencapai 12.000 pada tahun 2022.
Pun demikian di Jepang, yang meskipun dikenal sebagai rumah bagi 43.631 perusahaan berusia lebih dari 100 tahun [Teikoku Databank, 2024]. Sumber yang sama juga menyebut, ada sekira 2000 orang terserap ke dalam bisnis-bisnis ini tiap tahunnya, namun sayangnya, anggapan ini kini rungkad seiring gelombang tsunami kebangkrutan yang melanda negeri tersebut.
Perusahaan riset kredit, Tokyo Shoko mencatat jumlahnya melonjak 42,9% dari tahun sebelumnya Mei 2023 atau sekitar 1.009 perusahaan. Salah satu unit bisnis yang terkena arus deras tsunami kebangkrutan tersebut adalah Aoki Mannendo. Grup bisnis yang hampir 200 tahun terakhir bergerak membuat wagashi, atau manisan tradisional khas Jepang di Tokyo bagian timur. Ada juga Mitaniya, jaringan toko kelontong mirip warung Madura yang telah berdiri sejak tahun 1858 ini diketahui juga mulai terdengar bangkrut pada Juni 2024.
Problem mereka adalah soal kependudukan. Betapa banyak warga Jepang yang sudah masuk usia uzur, yang selain kesulitan menggunakan Ai juga kesulitan menghadapi risiko dalam penggunaannya.
Culture GRC
Kekhawatiran lain yang muncul di balik tsunami kebangkrutan di negara-negara di dunia adalah soal budaya. Terutama kemalasan [kasal,-red]. Dalam konteks Indonesia, tingginya optimisme terhadap ketersediaan Ai, bisa menjadi backfier.
Karena rupanya Ai selain berpotensi meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam bisnis, juga bisa menimbulkan risiko "kemalasan" atau ketergantungan berlebihan jika tanpa pengawasan yang tepat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi inisiatif manusia, mengakibatkan keputusan yang tidak etis, atau bahkan menyebabkan kesalahan besar.
Ilmuwan komputer terkemuka, sekaligus 'Bapak Ai" sedunia, Geoffrey Hinton, sampai harus pensiun dari Alphabet Inc. [induk perusahaan Google] lantaran khawatir bahwa AI akan menjadi teknologi yang tak terkendali.
Kata Hinton, akan sangat sulit mencegah aktor-aktor jahat dalam penggunaan AI. Pemenang Penghargaan Turing ini prihatin akan bahaya disinformasi yang dipicu foto, video, dan hoaks seperti terjadi di Inggris baru-baru ini.
Risiko-risiko ini sebetulnya bisa dimitigasi, misalnya dengan menerapkan tata kelola yang baik [Governance]. Berupa implementasi kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI adalah akurat, relevan, dan sesuai dengan regulasi privasi. Ini bisa mencegah AI membuat keputusan berdasarkan data yang salah atau bias.
Kita juga harus memastikan Transparansi Algoritma, bahwa algoritma AI yang digunakan dapat diaudit dan dipahami oleh manusia. Transparansi ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias atau kesalahan dalam sistem AI.
Mitigasi juga dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko [risk], terutama dengan melakukan penilaian risiko yang menyeluruh terhadap implementasi AI. Termasuk potensi ketergantungan yang berlebihan dan dampak negatif terhadap tenaga kerja manusia.
Pemantauan dan pengendalian wajib dilakukan, dengan cara melakukan pengembangkan mekanisme untuk terus memantau kinerja AI dan memastikan bahwa sistem ini beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Last, mitigasi risiko juga dapat dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi [compliance]. Bahwa siapa pun, institusi bisnis manapun harus memiliki etika dalam menggunakan Ai. Kita perlu memiliki kode etik yang ketat untuk menggunakan Ai. Sehingga kita bisa memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggungjawa dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Jika selama ini regulasi dibuat sendiri-sendiri, maka ke depan mestinya ada regulasi internasional mengenai penggunaan Ai. Termasuk hukum privasi data seperti GDPR di Eropa, untuk memastikan bahwa penggunaan Ai tak melanggar hukum.
Pada akhirnya, dalam dunia bisnis yang makin tergantung pada Ai, penerapan GRC [Governance, Risk, and Compliance] adalah kunci buat mengatasi risiko kemalasan dan memastikan bahwa teknologi Ai digunakan secara etis dan bertanggung jawab.
Budaya silo [enggan berbagi informasi] maupun malas [tidak mengukur sesuatu dalam angka] diharapkan dapat dihilangkan dengan budaya baru yaitu Governance, Risk, dan Compliance [GRC Culture]. Sistem nilai yang membentuk pola pikir [cognitive aspect], pola sikap [affective aspect], dan pola tindak [psychomotor aspect].
Budaya baru perusahaan yang dapat memastikan bahwa mereka tidak cuma menghindari kerugian, tapi juga memanfaatkan potensi penuh dari Ai untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan berkemajuan.
*Dosen pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, peserta konfrensi AI4 di Las Vegas