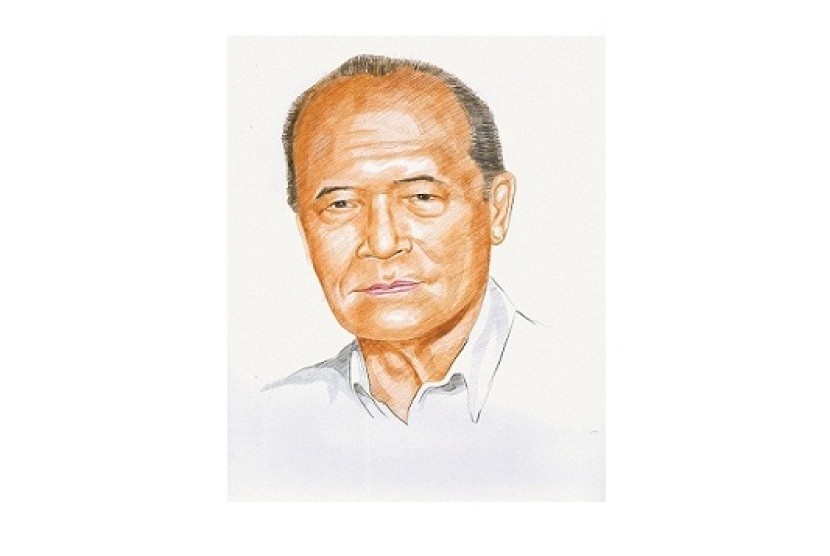REPUBLIKA.CO.ID, Dengan perantaraan dosennya DR Azhar Ibrahim, saya diminta memberikan kuliah umum di Jabatan Pengajian Melayu, Universitas Nasional Singapura, pada 13 Februari 2016. Istilah pengajian sama dengan kajian di Indonesia, sebab pengajian di sini punya konotasi sebagai ceramah agama.
Judul kuliah saya adalah “Tradisi Keagamaan dan Intelektual Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Tantangan Masa Kini)". Cukup banyak yang hadir di Perpustakaan Nasional Singapura itu, umumnya kaum intelektual Melayu, wartawan, dosen, seniman, mantan menteri, dan mahasiswa.
Kuliah dan diskusi berlangsung selama dua jam, kemudian dengan peserta yang terbatas dan santai diteruskan lagi di meja makan selama sekitar dua jam pula yang juga dihadiri mantan koresponden Berita Harian yang pernah bertugas selama lima tahun di Jakarta. Sahabat kita ini masih tetap mengikuti segala kejadian penting di Indonesia.
Diskusi berjalan lancar dan hidup, hampir tidak ada resistensi terhadap apa yang saya sampaikan, sekali pun juga menyangkut masalah-masalah kontroversi, seperti kotak Suni, kotak Syiah, mazhab dan nonmazhab, titik-titik lemah dunia Melayu Muslim, dan lain-lain sebagaimana sebagian pernah ditulis di harian ini.
Biasanya, umat Islam di Singapura atau Malaysia amat peka dengan isu-isu kontroversi. Mungkin karena yang hadir adalah kaum terdidik, suasananya menjadi tenang, penuh pengertian, tanpa gejolak emosi. Diskusi dalam iklim yang semacam ini sungguh menyenangkan, perbedaan pandangan dinilai sebagai sesuatu yang saling memperkaya.
Banyak yang menyalami saya usai diskusi, pertanda kuliah yang disampaikan mengenai sasarannya. Mantan menteri sambil menyalami saya mengatakan bahwa kuliah ini lucid (cerah, tenang). Tentu saja saya gembira bahwa apa yang disampaikan tidak menimbulkan kegaduhan dan hujatan.
Saya perhatikan wajah Ketua Jabatan Prof Dr Noor Aishah Abdul Rahman yang tenang dan antusias mengikuti kuliah umum. Artinya, intelektual Melayu/Muslim di Singapura sudah cukup dewasa berhadapan dengan pemikiran kaum intelektual Muslim kontemporer yang gelisah dalam upaya mencari jalan ke luar dari masalah-masalah keislaman yang kini sedang berada di tikungan yang terjal. Adapun DR Azhar Ibrahim, alumnus sebuah universitas di Kopenhagen (Denmark) dalam teologi sosial, bertindak sebagai moderator yang lincah.
Berikut ini adalah bagian dari kuliah umum itu. Di akhir “Resonansi” ini, dibicarakan pula gerakan intelektual Indonesia sebagai buah dari sistem pendidikan Barat yang tidak seluruhnya sama dengan isi kuliah umum itu.
Perjalanan sejarah nusantara sebelum terbentuknya Indonesia sebagai bangsa dan kemudian negara telah berlangsung dalam kurun yang panjang dan berliku. Sejak sekitar abad kelima Masehi, di Kutai (Kalimantan Timur) dan di Jawa Barat sudah dijumpai jejak kegiatan pemeluk agama Hindu dengan membentuk kerajaan-kerajaan lokal dengan nama rajanya masing-masing Mulawarman dan Purnawarman.
Jejak kegiatan pemeluk Buddha bahkan terjadi lebih awal di Jember dan di Palembang. (Lihat G Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, diedit oleh Walter F Vella dan diterjemahkan oleh Susan Brown Cowing. Honolulu: East-West Center Press, 1968, hlm 18).
Kedua agama yang berhulu di India itu kemudian selama berabad-abad telah menguasai alam pikiran nusantara, bahkan para penguasanya mendirikan kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Sumatra, seperti Sriwijaya dan Majapahit dengan peninggalan candi-candi besar yang dipelihara dengan baik sebagai warisan sejarah yang penting sampai hari ini.
Namun, sejak sekitar abad ke-13/ke-14 peran kedua agama tua itu secara berangsur surut digantikan oleh agama Islam sebagai pendatang baru. Belum ada satu teori pun yang memuaskan sampai sekarang yang menjelaskan mengapa pada akhirnya Islam memenangkan “pertarungan” lintas iman di panggung sejarah nusantara berhadapan dengan agama Buddha, Hindu, dan kemudian agama Kristen.